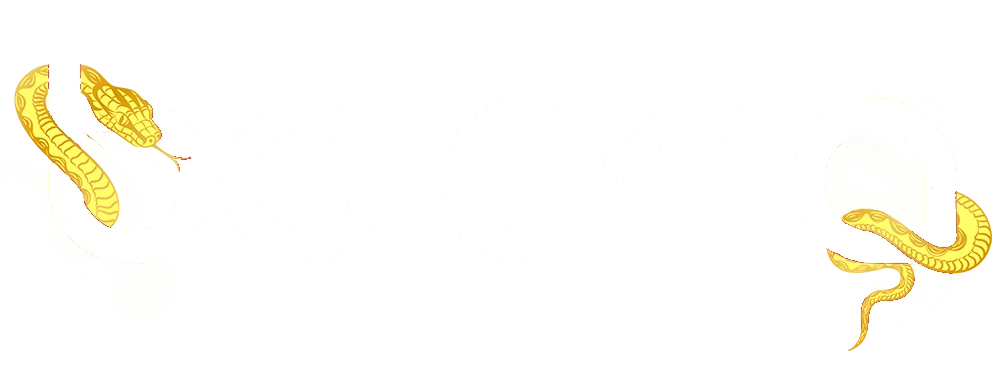* "Skenario terburuk kelaparan" saat ini sedang terjadi di Jalur Gaza.
* Ketika Gaza semakin terperosok ke dalam krisis kemanusiaan yang kian parah, peluang untuk tercapainya gencatan senjata tetap sangat kecil.
* Meski dorongan internasional untuk mengakui Negara Palestina semakin menguat, Presiden AS Donald Trump tetap menentangnya.
KAIRO, 7 Agustus (Xinhua) -- Hampir dua tahun konflik Palestina-Israel berlangsung, Gaza semakin terpuruk dalam penderitaan kelaparan dan pengepungan. Bantuan masih sangat terbatas, jumlah korban tewas terus meningkat, dan kelaparan bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan.
Terlepas dari desakan untuk segera melakukan intervensi, pembicaraan gencatan senjata terhenti, karena perpecahan yang mendalam terus berlanjut antara Hamas, Israel, dan para mediator internasional.
Semakin banyak negara Barat yang mengarah untuk mengakui Negara Palestina dengan harapan dapat mendorong diakhirinya bencana kemanusiaan ini. Namun, Washington, meski mengakui adanya kelaparan yang mengerikan di Gaza, tetap teguh mendukung Israel dan berpegang pada sistem bantuan yang kontroversial.
Ketika Gaza semakin terperosok ke dalam katastrofe kemanusiaan dan kebijakan Amerika Serikat (AS) tetap tidak berubah, tersisa satu pertanyaan: Masa depan seperti apa yang menanti setelah perang dan kelaparan?

Warga Palestina mengambil bantuan kemanusiaan di Beit Lahia, Jalur Gaza utara, pada 5 Agustus 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
KELAPARAN YANG MEMBURUK
Selama dua tahun, Gaza terus berjuang di ambang kelaparan, namun perkembangan terakhir "secara signifikan memperburuk" situasi, termasuk "blokade yang semakin ketat" oleh Israel, demikian menurut Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (Integrated Food Security Phase Classification/IPC), sebuah sistem standar global untuk menilai tingkat keparahan kerawanan pangan, pada Juli.
"Skenario terburuk kelaparan" saat ini sedang terjadi di Jalur Gaza, yang berpopulasi 2,3 juta jiwa, kata badan internasional untuk krisis pangan. Mereka memprediksi terjadi "kematian yang meluas" jika tidak ada tindakan segera.
Anak-anak menanggung beban terberat dari krisis ini, dengan angka malanutrisi yang terus meningkat ke arah yang mengkhawatirkan. Dari 74 kematian terkait malanutrisi pada 2025, 63 di antaranya terjadi pada Juli, termasuk 24 anak di bawah lima tahun (balita), seperti yang dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Secara keseluruhan, 180 orang, termasuk 93 anak-anak, meninggal dunia akibat kelaparan dan malanutrisi sejak Oktober 2023, kata otoritas kesehatan Gaza pada Senin (4/8).
"Tetesan bantuan harus berubah menjadi lautan (bantuan)," desak Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. "Makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar harus mengalir tidak berkeputusan dan tanpa hambatan."
Terlepas dari seruan tersebut, upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan masih sangat tidak memadai. Meskipun Israel telah mengizinkan pengiriman bantuan via udara secara terbatas dan beberapa konvoi bantuan, bantuan yang masuk ke Gaza masih belum mencukupi, demikian ungkap Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA). Konvoi-konvoi terus menghadapi rintangan dan bahaya di sepanjang rute yang dipetakan oleh otoritas Israel.
Sementara itu, banyak warga dilaporkan terus menjadi korban tewas dan terluka saat berusaha mendapatkan makanan. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR) pada Jumat (1/8) mengatakan bahwa 1.373 pencari bantuan tewas di Jalur Gaza sejak akhir Mei, sebagian besar tewas oleh militer Israel.

Warga Palestina menunggu untuk menerima makanan gratis dari pusat distribusi makanan di Gaza City pada 2 Agustus 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
PERUNDINGAN TERHENTI
Ketika Gaza semakin terperosok ke dalam krisis kemanusiaan yang kian parah, peluang untuk tercapainya gencatan senjata tetap sangat kecil.
Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (31/7), Hamas menegaskan kembali kesediaannya melanjutkan perundingan untuk gencatan senjata permanen dan penarikan mundur Israel secara penuh, namun hanya jika krisis kemanusiaan di Gaza mengalami perbaikan yang signifikan.
"Sangat penting untuk memperbaiki situasi kemanusiaan yang sangat buruk ini secara signifikan dan untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pihak musuh mengenai respons kami," ujar Basem Naim, seorang pejabat senior Hamas, kepada CNN. "Ini adalah syarat untuk kembali ke perundingan."
Kelompok ini juga menolak saran demiliterisasi, menyatakan bahwa hanya pemulihan penuh hak-hak nasional Palestina yang dapat menghasilkan kompromi.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin mengatakan dirinya akan mengarahkan tentara Israel akhir pekan ini untuk mencapai tiga tujuan perang "tanpa terkecuali" di Gaza, yakni "mengalahkan musuh, membebaskan para sandera, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi mengancam Israel."
Dalam kunjungan regional baru-baru ini, utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, juga menekankan perlunya pergeseran dalam negosiasi, dari perjanjian bertahap menjadi kesepakatan komprehensif yang akan membebaskan semua sandera sekaligus.
Berbicara dengan keluarga para sandera pada Sabtu (2/8), dia juga mengatakan bahwa Hamas "siap untuk didemiliterisasi," menurut surat kabar Israel, Haaretz.

Warga Palestina berkabung untuk seorang korban, yang tewas dalam serangan udara Israel, di sebuah rumah sakit di Gaza City pada 4 Agustus 2025. (Xinhua/Mahmoud Zaki)
AS DUKUNG ISRAEL
Seiring beredarnya foto-foto anak-anak yang kurus kering di Gaza ke seluruh dunia, semakin banyak negara Barat yang bergerak untuk secara resmi mengakui Negara Palestina, termasuk Prancis, Inggris, Kanada, Portugal, Malta, dan juga beberapa negara lainnya.
Meski dorongan internasional untuk mengakui Negara Palestina semakin menguat, Presiden AS Donald Trump tetap menentangnya. Trump, yang mengakui adanya kerawanan pangan di Gaza, mengirim utusan Timur Tengahnya ke Israel untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir di tengah meningkatnya keprihatinan internasional mengenai mekanisme distribusi bantuan.
Kendati demikian, kunjungan Witkoff ke lokasi Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation) yang kontroversial memicu kritik mengenai dukungan berkelanjutan Washington terhadap model bantuan yang bermasalah itu. Para analis berpendapat bahwa bukannya menjadi perantara yang imparsial, AS lebih berfungsi sebagai pendukung ambisi militer Israel, yang lebih memprioritaskan politik daripada perdamaian.
"AS semakin terlihat tidak sejalan dengan masyarakat internasional, terutama dalam hal dukungannya yang tanpa syarat untuk Israel," kata Ayman Yousef, profesor ilmu politik di Arab American University di Ramallah, kepada Xinhua.
"Meskipun AS tetap menjadi kekuatan global yang dominan, posisinya di Palestina menghancurkan legitimasi dan kredibilitasnya," tambah Yousef.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan tentang situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, di kantor pusat PBB di New York pada 5 Agustus 2025. (Xinhua/UN Photo/Loey Felipe)
Menyuarakan keprihatinan yang sama, Ghassan Khatib, profesor hubungan internasional di Universitas Birzeit di Ramallah, mengatakan bahwa meski diterpa kecaman global yang belum pernah terjadi sebelumnya, AS "terus melindungi Israel secara diplomatis dan militer."
"Jika tekanan internasional dan kemarahan publik terus meningkat, terutama di kalangan masyarakat Barat, AS pada akhirnya akan menyadari bahwa sikapnya saat ini tidak dapat dipertahankan," katanya.
Will Todman, peneliti senior di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, mengatakan bahwa dukungan AS yang terus berlanjut bagi pemerintah Israel "telah melindungi Israel dari tekanan internasional."
Dengan dukungan tersebut, pemerintah Israel "kemungkinan tidak akan mengubah prioritas strategisnya di Gaza," katanya.
"Kredibilitas AS telah rusak parah, dan secara operasional AS kini berada dalam posisi yang sangat terbatas akibat kebijakan yang diberlakukannya sendiri, sehingga kemampuannya untuk memberikan bantuan yang berarti bagi warga Gaza sangat berkurang," tulis J. Stephen Morrison dan Leonard Rubenstein dari Pusat Kebijakan Kesehatan Global di Pusat Kajian Strategis dan Internasional dalam sebuah artikel. Selesai
Advertisement