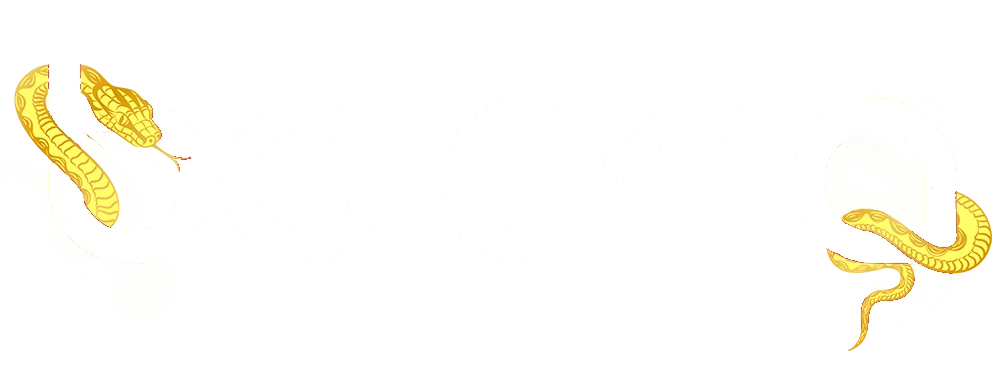Bolong.id - Opini - Perayaan Imlek bukan sekadar penanda pergantian kalender lunar dalam tradisi Tionghoa, melainkan sebuah peristiwa kebudayaan yang sarat makna historis, filosofis, dan sosial. Ia hidup sebagai ruang ingatan kolektif tentang asal-usul, tentang harapan, dan tentang relasi antarmanusia yang dipererat melalui simbol, ritus, dan kebersamaan. Dalam konteks Indonesia, Imlek memiliki resonansi yang lebih luas dan menjelma menjadi cermin perjalanan panjang bangsa dalam merawat toleransi di tengah kemajemukan.
Secara kultural, Imlek berakar pada kosmologi agraris Tiongkok kuno. Pergantian tahun dipahami sebagai siklus alam. Musim berganti, panen diharapkan, dan kehidupan diperbarui. Tradisi membersihkan rumah, memasang lampion merah, membagikan angpao hingga makan malam keluarga bukanlah seremoni kosong, melainkan simbol pembaruan moral meninggalkan kesialan, menyongsong keberuntungan, serta mempererat ikatan genealogis.
Warna merah melambangkan proteksi dan sukacita; kue keranjang menandai kontinuitas rezeki. Dimana barongsai merepresentasikan penolak bala. Simbolisme ini membangun narasi bahwa manusia hidup dalam jaringan harmoni antara langit, bumi, dan sesama.
Namun, ketika tradisi ini berlayar melintasi ruang diaspora termasuk ke Nusantara. Ia mengalami proses akulturasi. Interaksi dengan budaya lokal melahirkan ekspresi khas yaitu perpaduan ornamen Tionghoa dengan arsitektur Melayu, sajian kuliner yang mengadopsi rempah Nusantara, hingga praktik peribadatan yang berdialog dengan tradisi setempat. Di titik ini, Imlek tidak lagi berdiri sebagai identitas eksklusif, melainkan sebagai identitas yang bernegosiasi mencari titik temu dengan realitas sosial Indonesia yang majemuk.
Sejarah mencatat bahwa perjalanan Imlek di Indonesia tidak selalu lapang. Pada periode tertentu, ekspresi budaya Tionghoa mengalami pembatasan struktural. Perayaan dilakukan secara terbatas, bahkan tersembunyi di ruang domestik. Bahasa, aksara, dan simbol-simbol kultural ditekan dari ruang publik. Situasi ini membentuk memori kolektif tentang keterpinggiran bahwa identitas budaya dapat menjadi rentan ketika berhadapan dengan konfigurasi politik kekuasaan.
Momentum reformasi mengubah lanskap tersebut. Pengakuan kembali terhadap Imlek sebagai hari libur nasional menandai rehabilitasi kultural sekaligus politik. Negara, dalam hal ini, mengafirmasi bahwa ekspresi budaya adalah hak warga, bukan privilese yang dapat dicabut. Sejak saat itu, Imlek hadir terbuka di ruang publik: lampion menghiasi jalan, pertunjukan barongsai tampil di pusat kota, dan masyarakat lintas etnis turut merayakan. Transformasi ini bukan sekadar administratif, melainkan simbol rekonsiliasi historis.
Dalam perspektif sosiologis, perayaan Imlek di Indonesia memperlihatkan bagaimana budaya dapat menjadi medium toleransi. Toleransi tidak lahir dari slogan normatif, melainkan dari interaksi keseharian. Ketika masyarakat non-Tionghoa ikut menyaksikan barongsai, mencicipi hidangan khas, atau mengunjungi rumah kerabat yang merayakan, terjadi proses pengenalan dan dari pengenalan lahir pemahaman. Budaya bekerja sebagai bahasa universal yang melampaui sekat identitas formal.
Lebih jauh, Imlek juga merepresentasikan etika Konfusian tentang harmoni sosial. Nilai “ren” (kemanusiaan), “yi” (kebajikan), dan “li” (kepantasan) tercermin dalam praktik saling memberi, menghormati orang tua, serta menjaga relasi kekeluargaan. Nilai-nilai ini bersifat lintas budaya; ia menemukan padanan dalam falsafah Nusantara seperti gotong royong dan tepa selira. Di sinilah toleransi menemukan fondasi etiknya kesadaran bahwa setiap tradisi mengajarkan kebaikan yang dapat dipertemukan.
Dalam konteks kebangsaan, Imlek memperkaya mozaik Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia tidak dibangun dari homogenitas, melainkan dari koeksistensi identitas. Setiap perayaan etnis termasuk Imlek berfungsi sebagai penanda bahwa kebangsaan Indonesia bersifat inklusif. Negara tidak meniadakan perbedaan, tetapi mengelolanya dalam kerangka persatuan. Oleh karena itu, merawat Imlek sama artinya dengan merawat prinsip pluralisme itu sendiri.
Dimensi ekonomi-budaya juga patut dicermati. Perayaan Imlek menggerakkan sektor pariwisata, industri kreatif, hingga UMKM. Produksi lampion, dekorasi, busana tradisional, kuliner khas, serta pertunjukan seni menciptakan ekosistem ekonomi musiman yang signifikan. Kota-kota dengan komunitas Tionghoa kuat sering memanfaatkan momentum ini sebagai festival budaya terbuka. Dampaknya bukan hanya finansial, tetapi juga diplomasi kultural menampilkan Indonesia sebagai ruang toleransi yang hidup.
Meski demikian, toleransi tidak boleh dipahami sebagai kondisi final. Ia adalah proses yang harus terus dirawat. Globalisasi digital membawa tantangan baru seperti misinformasi, stereotip etnis, hingga politisasi identitas dapat dengan cepat menyebar. Dalam situasi demikian, perayaan budaya seperti Imlek memiliki fungsi strategis sebagai kontra-narasi menunjukkan secara konkret bahwa koeksistensi harmonis bukan utopia, melainkan realitas yang telah dipraktikkan.
Pendidikan multikultural menjadi instrumen penting. Generasi muda perlu memahami sejarah Imlek di Indonesia, termasuk fase-fase pembatasan dan rehabilitasinya. Kesadaran historis ini mencegah amnesia kolektif bahwa toleransi yang dinikmati hari ini adalah hasil perjuangan panjang. Tanpa pemahaman sejarah, toleransi mudah tereduksi menjadi seremoni tanpa makna.
Di tingkat praksis, toleransi juga tercermin dalam partisipasi lintas iman dan etnis saat Imlek. Aparat keamanan menjaga vihara, pemerintah daerah memfasilitasi festival, dan masyarakat sekitar turut membantu kelancaran perayaan. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa toleransi bekerja melalui institusi sekaligus komunitas. Ia bukan hanya sikap personal, tetapi juga tata kelola sosial.
Akhirnya, Imlek mengajarkan bahwa budaya adalah jembatan bukan tembok. Ia menghubungkan masa lalu dengan masa kini, diaspora dengan tanah air, serta perbedaan dengan persatuan. Dalam setiap lampion yang menyala, terdapat harapan akan terang kebersamaan. Dalam setiap angpao yang dibagikan, tersimpan doa tentang kesejahteraan bersama. Dan dalam setiap perjamuan keluarga, terpatri nilai bahwa harmoni dimulai dari relasi yang paling dekat.
Indonesia, sebagai bangsa majemuk, membutuhkan lebih banyak ruang-ruang kultural semacam ini. Ruang di mana identitas tidak dipertentangkan, melainkan dirayakan. Imlek telah menunjukkan preseden bahwa perbedaan dapat hidup berdampingan tanpa kehilangan keaslian masing-masing. Toleransi, pada akhirnya, bukan tentang menghapus identitas, tetapi tentang mengakui, menghormati, dan merawatnya dalam satu rumah kebangsaan.
Dengan demikian, merayakan Imlek sejatinya adalah merayakan Indonesia sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman, dipersatukan oleh penghormatan, dan dikuatkan oleh toleransi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. (msf)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement