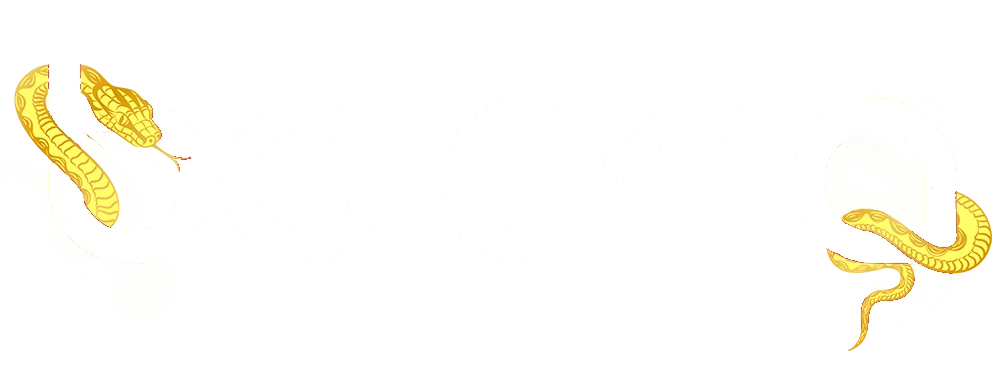Bolong.id - Bahasa Indonesia tak hanya bertahan di tanah air, tapi juga tumbuh di kampus-kampus China. Di balik dinding universitas di Guangdong, kata-kata dari Nusantara menggema sebagai jembatan persahabatan antarbangsa.
Di sebuah ruang kelas di Guangdong University of Foreign Studies (GUFS), suara pelan terdengar dari balik papan tulis. “Selamat pagi… apa kabar?” ucap seorang mahasiswa China dengan logat khas Mandarin. Di hadapannya, Xiao Lixian, atau yang akrab disapa Melati, tersenyum sambil mengangguk pelan. “Bagus sekali. Ucapannya sudah hampir sempurna,” katanya dalam Bahasa Indonesia yang fasih.
Pagi itu, kelas Bahasa Indonesia tampak hidup. Mahasiswa-mahasiswi muda dari berbagai daerah di China Selatan membaca teks, menulis kalimat sederhana, hingga mempraktikkan percakapan sehari-hari. Di luar jendela, bunga sakura khas Guangdong mulai bermekaran kontras dengan kata-kata “selamat datang”, “terima kasih”, dan “sampai jumpa” yang keluar dari bibir para penutur baru bahasa dari negeri tropis ribuan kilometer jauhnya.
Dari Pembekuan Diplomatik ke Lahirnya Jurusan
Perjalanan Bahasa Indonesia di China tak selalu semulus laju kereta cepat. Pada era 1950-1970, hubungan diplomatik Indonesia-China sempat membeku akibat ketegangan politik pasca Gerakan 30 September 1965. Akibatnya, minat masyarakat Tionghoa untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia merosot tajam.
Namun, di tengah suhu politik yang dingin itu, Presiden Mao Zedong justru memandang jauh ke depan. Ia menilai Bahasa Indonesia sebagai bahasa penting di kawasan Asia Tenggara, dan karena itu perlu diajarkan di kampus. Maka pada tahun 1970, berdirilah Jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa-bahasa Asing Guangdong, menjadi simbol diplomasi budaya di tengah keterasingan politik.
Langkah tersebut menjadi awal dari perjalanan panjang yang hari ini melahirkan sekitar 20 universitas di seluruh China yang memiliki program studi Bahasa Indonesia dari Shanghai, Tianjin, Yunnan, hingga Guangxi.
Kemitraan Strategis yang Menghidupkan Bahasa
Kebangkitan minat terhadap Bahasa Indonesia mencapai momentum baru pada tahun 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao menandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis Indonesia-China. Sejak saat itu, semakin banyak universitas yang membuka jurusan baru.
GUFS di Guangdong menjadi salah satu pelopornya. Menurut Melati, dosen yang pernah menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, jumlah mahasiswa yang mengambil jurusan Bahasa Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Dulu hanya 10-20 orang per angkatan. Sekarang jumlahnya stabil, dan peminatnya datang bukan hanya dari Guangdong, tapi juga dari Guangxi dan Fujian,” katanya.
Lulusan jurusan ini kini tersebar di berbagai bidang dari penerjemah di perusahaan China yang berinvestasi di Indonesia, staf KJRI, hingga pegawai pemerintahan. Permintaan terhadap tenaga ahli berbahasa Indonesia terus meningkat seiring intensifnya hubungan dagang dan investasi kedua negara.

Dari Kelas Bahasa ke Diplomasi Budaya
Di GUFS, bahasa bukan sekadar mata kuliah, tetapi juga pintu masuk menuju pemahaman lintas budaya. Setiap dua tahun, kampus ini menerbitkan “Buku Biru Indonesia” laporan akademis lintas disiplin yang memotret kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia terkini.
Tahun ini, GUFS juga bersiap menggelar Festival Indonesia pada 23 November 2025, menghadirkan delegasi dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Indonesia (UI). Akan ada lokakarya batik, pameran kuliner, serta pertunjukan tari tradisional.
“Lewat festival ini, kami ingin masyarakat Guangdong mengenal Indonesia lebih dekat,” ujar Melati.
Ketika Mahasiswa China Jatuh Cinta pada Indonesia
Daya tarik Indonesia bagi mahasiswa China bukan semata akademis, tapi juga emosional. Wang Qi, mahasiswi GUFS yang akrab disapa Afiya, bercerita bahwa ketertarikannya pada Bahasa Indonesia tumbuh setelah kunjungan wisata ke Surabaya dan Bali.
“Saya melihat budaya yang unik dan orang-orang yang sangat ramah. Dari situ saya ingin belajar Bahasa Indonesia,” ujarnya sambil tersenyum.
Rekan sekelasnya, Sheng Zhe atau Seviana, memiliki alasan serupa. Ia jatuh cinta pada keindahan dan spiritualitas budaya Bali. “Bahasa Indonesia terasa lembut dan mudah diucapkan. Rasanya seperti berbicara dari hati,” katanya.
Baik Afiya maupun Seviana menilai bahwa Bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari dibandingkan Bahasa Inggris, terutama karena pelafalannya yang konsisten. “Kami mulai dari huruf, lalu kata, lalu kalimat. Dosen-dosen kami sangat sabar membimbing,” tutur Afiya.
Bahasa sebagai Jembatan dan Benteng
Dari ruang kelas di Guangdong, gema Bahasa Indonesia terdengar hingga ke hati para pembelajarnya. Di balik semua itu, tersimpan pelajaran penting: bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan jembatan antarbudaya.
Di saat yang sama, bagi bangsa Indonesia sendiri, Bahasa Indonesia adalah benteng pertama dalam pertahanan budaya. Dalam derasnya arus globalisasi, penggunaan bahasa baku yang baik dan benar di ruang publik, media, dan pendidikan menjadi kunci menjaga jati diri nasional.
Bahasa gaul dan bahasa daerah boleh berkembang, tapi Bahasa Indonesia harus tetap menjadi fondasi kokoh persatuan bahasa yang mampu menampung ribuan logat, tapi tetap menyuarakan satu identitas Indonesia.
Ketika Melati menatap mahasiswa-mahasiswanya melafalkan “Saya cinta Bahasa Indonesia”, ada cahaya kecil yang menyala di matanya. Mungkin, di antara ratusan ribu kata yang diucapkan di ruang kelas itu, tersimpan makna yang lebih dalam, bahwa cinta pada bahasa adalah cinta pada kemanusiaan, dan lewat kata-kata, bangsa bisa saling memahami. (*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement